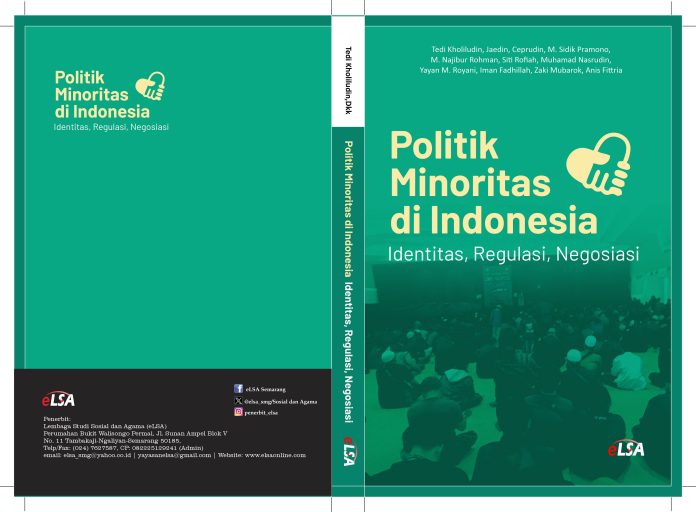Fadli Rais (Redaktur elsaonline.com)
Malam itu, di sebuah kota kecil di Jawa, seorang mahasiswi muda mengetuk pintu rumah kos. Pemilik kos menyambut ramah, menanyakan asal-usul, lalu agama yang dianut.
“Syiah,” jawabnya jujur. Senyum ramah di wajah pemilik kos bikin muram perempuan berhijab kala mulut pemilik kos meluncurkan ucapan
“Maaf, kami tidak bisa menerima.”
Mulut mahasiswa tak ingin mengumpat, pilihan pergi dengan langkah gontai dan perut mual. Peristiwa penolakan bukan kali pertama ia alami. Perempuan, muda, dan Syiah dipikulnya tiga lapis identitas karena sering dianggap menyimpang dari norma mayoritarian. Alih-alih menyerah, ia bersolidaritas bersama teman-temannya membangun komunitas kecil guna berbagi ruang, berbagi cerita, hingga ritual sederhana. Berkumpul membuat ruang aman menemukan kekuatan untuk bertahan (hlm. 221).
Kisah nyata ini menggambarkan realitas pada buku Politik Minoritas di Indonesia: Identitas, Regulasi, Negosiasi (eLSA Press, 2025). Ibarat bermain bola, karya ini digarap sebelas penulis lintas disiplin dengan menghadirkan wajah lain demokrasi Indonesia. Gambaran minoritas lebih dari sekadar angka kecil dalam angka, melainkan manusia berjalan pada kerentanan sekaligus berlatih kreativitas.
Tedi Kholiludin, pada bab pembuka memperkenalkan kerangka sosiologi minoritas keagamaan. Dosen Universitas Wahid Hasyim menarasikan minoritas lahir dari tiga proses: diferensiasi, diskriminasi, dan kesadaran kolektif (hlm. 10). ”Label” status minoritas tidak otomatis terkait jumlah. Kristen pribumi di Jawa, misalnya, pernah mendapat akses politik luas di masa kolonial, tetapi pasca kemerdekaan justru tersingkir, bahkan terusir dari Cigelam, Bekasi, pada 1945 (hlm. 12).
Kerangka tulisan berjudul Sosiologi Minoritas Keagamaan: Dari Diferensiasi dan Minoritisasi ke Politik “Becoming-Minoritarian diperluas dengan teori interseksionalitas Kimberlé Crenshaw pada karya Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color menjelaskan kerentanan berlapis. Perempuan penghayat kepercayaan jadi contoh keseharian harus berhadapan dengan diskriminasi ganda. Dilahirkan dan hidup sebagai perempuan sekaligus penganut kepercayaan yang lama tak diakui negara.
Uraian pada tulisan pria kelahiran Kuningan, juga meminjam becoming-minoritarian milik Deleuze dan Guattari. Menjadi minoritas bukanlah keadaan pasif, melainkan proses aktif melampaui jerat mayoritarian. Perjuangan penghayat kepercayaan yang membawa kasus ke Mahkamah Konstitusi pada 2017 adalah contoh gamblang. Setelah puluhan tahun dipaksa mengosongkan kolom agama di KTP, MK akhirnya mengabulkan gugatan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim (hlm. 34). Putusan tak hanya dilihat sekadar legal victory, ada upaya “deterritorialisasi” guna membuka ruang pengakuan baru di luar kerangka enam agama resmi.
Sudut pandang tulisan di buku Politik Minoritas di Indonesia bergerak lebih jauh dari laporan tahunan intoleransi. Ajakan kepada pembaca menyelami minoritas sebagai konstruksi sosial-politik yang dinamis, sekaligus agen dengan kemampuan mengubah kondisi.
Negara dan Wajah Ambivalen Kekuasaan
Kumpulan pasal konstitusi menjamin kebebasan beragama hanya di atas kertas, praktik sehari-hari menunjukkan ambivalensi negara a.k.a di-php-in. Birokrasi mestinya netral justru memperkuat diskriminasi.
Kasus penolakan pembangunan gereja di Pegambiran, Cirebon jadi salah contoh kasus. Fakta lapangan jemaat telah memenuhi syarat administratif, izin mendirikan rumah ibadah tetap ditolak dengan alasan “belum ada kesepakatan masyarakat” (hlm. 24). Aparat negara justru memilih menyerahkan keputusan kepada mayoritas. Gereja tidak pernah berdiri. Konstitusi tak berdaya digruduk keinginan massa. Aturan rumah ibadah lebih menyenangkan dibaca ketimbang ditegakkan untuk memenuhi umat di Pegambiran.
Pembangunan Pegambiran tak sendirian, pengalaman buruk dialami penghayat kepercayaan. Sebelum putusan MK 2017, mereka tidak bisa mencatat pernikahan, sulit mengakses pendidikan agama sesuai keyakinannya, bahkan mengalami diskriminasi administratif saat mengurus dokumen (hlm. 27). Hidup bertahun-tahun di tanah kelahiran berpegangan pada identitas mereka sah sebagai warga, tetapi dianggap “tidak sah” di mata negara.
Akrobat negara semakin nyata ketika Presiden Jokowi, pada 11 Januari 2023, mengakui 12 pelanggaran HAM berat. “Saya menyesalkan,” katanya. Pengakuan ini penting, tetapi tanpa mekanisme yudisial, ia berisiko hanya menjadi penyesalan simbolik. M. Najibur Rohman tulisan Noktah Merah Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia menilai pengakuan semacam ini berpotensi melanggengkan impunitas (hlm. 92). Negara hadir, tetapi sebatas retorika.
Nnoktah merah yang tak pernah benar-benar hilang saban pelanggaran HAM berat yang dibiarkan membekas tanpa pemulihan. Negara berulang kali menyatakan hadir, menegaskan komitmen untuk menuntaskan masa lalu. Cuma hadirnya ya lebih sering berupa retorika ketimbang tindakan nyata. Pas pidato resmi menggaungkan janji, namun di lapangan korban tetap menunggu, keluarga tetap berduka, dan kebenaran masih terkubur.
Noktah merah terus melekat saban hari, berubah menjadi ingatan kolektif dengan menyala bak api menolak padam. Korban menegaskan bahwa tanpa keberanian menghadirkan kebenaran dan keadilan, kehadiran Negara hanya akan tercatat sebagai gema kosong. Retorika tak pernah menghapus darah, tak pernah mengeringkan air mata.
Siti Rofiah memotret Komunitas Support Group Sekartaji di Semarang. Di ruang aman, perempuan penyintas KDRT menemukan kekuatan untuk pulih, berbagi, dan bangkit kembali. Mereka menenun solidaritas yang memberi mereka “rumah” baru (hlm. 114–116). Kisah ini mempertontonkan paradoknya negara yang absen, komunitas justru mengambil alih peran pelindung. Para pekerja rumah tangga menjadi tulang punggung ekonomi keluarga kelas menengah, PRT tetap tak dilindungi hukum. RUU Perlindungan PRT berulang kali disuarakan pun berulang kali tersendat di DPR. Menurut Muhamad Nasrudin, ini cermin kegagalan negara dalam melindungi warga yang paling rentan (hlm. 133).
Rentetan peristiwa ini menguatkan satu hal: negara hadir, tetapi condong sebelah. Alih-alih menjadi wasit yang adil, pemerintah kerap tunduk pada tekanan mayoritas atau memilih jalan paling aman sambil mengiris perlahan hak-hak minoritas.
Dari Korban ke Subjek Negosiasi
Pembaca akan tertarik pada pada bagian ketiga. Di buku ini menampilkan minoritas bukan sekadar korban, melainkan aktor yang berdaya.
Iman Fadhillah menyoroti pemikiran Khaled Abou El Fadl menggunakan pendekatan literary criticism. Penolakan Abou El Fadl pada tafsir otoritarian kerap kali menghantam minoritas melalui justifikasi diskriminasi. Inskripsi tafsir inklusif ini memberi napas baru bagi kelompok rentan, terutama perempuan (hlm. 203).
Zaki Mubarok menulis tentang kiai desa yang menjaga Pancasila. Repertoar kiai menghadapi tantangan dari “santri baru” yang berpegang pada faham puritan dan populisme politik yang mengikis otoritas kiai tradisional. Strategi mereka bukan konfrontasi, melainkan delegasi dan mediatisasi kala mengutus santri sebagai jembatan konflik, serta memanfaatkan media lokal untuk meneguhkan nilai kebangsaan (hlm. 220).
===
Putar balik ke kisah perempuan muda Syiah. Setelah berulang kali ditolak, ia dan teman-temannya membangun komunitas kecil. Mereka berbagi ruang tinggal, berbagi dapur, bahkan melaksanakan ritual Asyura dengan sederhana dan hati-hati. Ya betul dengan hati-hati yang dilatih saban hari. Mulai hal-hal kecil inilah lahir solidaritas dan kekuatan (hlm. 236).
Perilaku sehari-hari sejalan dengan konsep James C. Scott di buku Weapons of the Weak. Perlawanan tidak selalu berupa demonstrasi besar atau gugatan hukum. Ia hadir dalam latihan sehari-hari berupa memilih siapa yang diajak tinggal bersama, berbagi makanan, atau sekadar saling menyapa.
Membandingkan dan Mengkritisi
Buku ini mengingatkan bahwa minoritas tidak bisa selamanya diposisikan sebagai korban pasif. Mereka adalah aktor kreatif yang terus menegosiasikan hidupnya. Kara Politik Minoritas di Indonesia menempati posisi penting dan tidak berdiri sendiri. Ada jejak-jejak karya sebelumnya yang perlu dijadikan cermin pembanding, sekaligus titik tolak untuk menilai apa yang ditawarkan buku ini.
Kita ingat Franz Magnis-Suseno dengan Etika Politik (1987). Buku klasik itu menekankan kewajiban moral negara untuk melindungi semua warga negara di dalamnya ada minoritas. Dibandingkan itu, Politik Minoritas terasa lebih membumi: penuh dengan kisah lapangan, dengan wajah-wajah nyata para penyintas menghadapi sehari-hari mengalami diskriminasi.
Karya lainnya milik, Budhy Munawar-Rachman melalui Pluralisme, Konflik, dan Perdamaian (2006) menawarkan telaah pluralisme yang tajam, terutama dalam konteks relasi agama-agama besar di Indonesia. Pada buku ini, Budhy jarang menyentuh minoritas di dalam tubuh Islam sendiri. Di situlah buku Politik Minoritas memberi kontribusi berupa menghadirkan suara Syiah, Ahmadiyah, atau bahkan penghayat kepercayaan yang lama tersisih.
Bandingkan dengan Expressing Islam (2008) karya suntingan Greg Fealy dan Sally White, terdapat perbedaan mencolok segera terlihat. Fealy dan White menempatkan pengalaman Islam Indonesia dalam horizon global, menghubungkannya dengan tren internasional. Buku Politik Minoritas, sebaliknya, lebih fokus ke konteks lokal dan kisah domestik. Kedalaman refleksi tentang agensi minoritas terasa kuat, tetapi perspektif perbandingan lintas negara masih terbatas.
Laporan tahunan Setara Institute atau Wahid Institute juga patut diingat. Dokumentasi yang kaya data kuantitatif mengumpulkan angka intoleransi, tren penyerangan, statistik rumah ibadah yang ditutup. Pada laporan tahuan pembaca disuguhi peta luas intoleransi Indonesia, tetapi tanpa refleksi teoretis yang mendalam. Politik Minoritas justru hadir di sisi sebaliknya: menawarkan kerangka konseptual segar dan narasi empirik, tetapi kurang menyajikan data longitudinal yang bisa memperlihatkan tren secara jelas.
Dari perbandingan ini, kita bisa melihat beberapa kelemahan buku Politik Minoritas di Indonesia. Pertama, ia kurang menautkan diri dengan wacana global. Kasus Rohingya di Myanmar atau Muslim sebagai minoritas di Eropa, misalnya, nyaris tak mendapat tempat. Padahal, perbandingan itu bisa memperkaya perspektif. Kedua, gaya penulisan antar-bab terasa timpang: ada yang sangat teoretis dengan jargon filsafat, ada yang naratif dan ringan. Perbedaan ini membuat alur bacaan tidak selalu mulus. Ketiga, buku ini miskin angka. Narasi kualitatifnya hidup, tetapi tanpa statistik, pembaca kesulitan melihat tren intoleransi secara utuh. Terakhir, ada isu-isu minoritas lain, seperti kelompok keragaman seksual kemunculannya sekilas, padahal dalam kenyataan sosial mereka menghadapi tekanan serupa, bahkan lebih berat.
Buku ini tetap menjadi pijakan berharga untuk memahami minoritas di Indonesia untuk membuka jalan, memberi bahasa, dan menajamkan lensa untuk membaca kerentanan sekaligus strategi kelompok minoritas dalam ruang sosial kita yang penuh tarik-menarik. Politik Minoritas di Indonesia: Identitas, Regulasi, Negosiasi menghadirkan wajah pluralisme Indonesia yang sering disembunyikan di balik jargon toleransi. Demokrasi tidak diukur dari suara mayoritas, melainkan dari sejauh mana yang kecil tetap dilindungi.
Di tengah menguatnya populisme dan mayoritarianisme, buku ini menjadi pengingat keras: demokrasi hanya bisa hidup jika yang kecil tetap mendapat ruang. Minoritas bukan sekadar angka, bukan sekadar korban, melainkan subjek politik yang ikut menentukan arah bangsa. So, baca dan sebarkan buku ini dengan mengunduh pada pranala ini.